Hampir semua media massa pada Selasa (20 Maret 2012) memberitakan aksi kelompok Sedulur Sikep Klopoduwur, atau yang dikenal dengan Kelompok Samin di Kantor Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Mereka meminta aksi damai meminta semua elemen bangsa untuk kembali pada nilai-nilai kejujuran.
Memang menarik mencermati seruan mereka: “Kejujuran adalah jalan utama yang kali pertama harus dilakoni. Kejujuran pada diri sendiri, kejujuran pada alam, dan kejujuran pada liyan. Aksi itu didasari keprihatinan bahwa nilai-nilai kejujuran sudah memudar, bahkan lenyap, sehingga timbul penyakit kronis yang menyerang bangsa Indonesia, yakni terutama adalah korupsi.
Kejujuran sudah menjadi kegelisahan manusia selama ribuan tahun. Marcus Aurelius, filsuf pada masa 121-180 Sebelum Masehi, mengungkapkan persoalan kejujuran itu dalam kalimat ”Jangan lakukan sesuatu yang tidak benar, jangan katakan sesuatu yang tidak benar.”
Sejujurnya pula, bukan hanya kelompok Samin itu pula yang prihatin tentang kejujuran. Entah sudah berapa kotbah Jumatan atau homili Minggu atau sarasehan-sarasehan kebatinan yang mengingatkan manusia untuk tetap berpegang pada kejujuran. Tetapi, rasa-rasanya kejujuran semakin jauh dari capaian manusia.
Dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi antaranggota keluarga, atau relasi dengan sahabat, mungkin nilai kejujuran relatif masih terjaga meski tidak 100 persen. Namun, dalam kehidupan politik, kejujuran seakan-akan tenggelam dalam hasrat mengejar dan mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, manusia politik berperilaku berdasarkan putaran mesin politik yang lepas dari nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kejujuran. Apakah kejujuran dalam politik hanya fatamorgana atau fantasi kita semua? Sesuatu yang tidak mungkin tercapai?
George Orwell, seorang satiris politik dan penulis novel klasik Animal Farm dan 1984 sudah mencurigai hal itu. Berdasarkan pengamatannya, dia yakin bahwa fungsi sesungguhnya dari pidato politik adalah untuk menyembunyikan, memperlunak, atau memelintir kebenaran. Dia menulis, ”Bahasa politik – dan dengan berbagai variasi yang mewujud dalam seluruh partai politik mulai dari konservatif hingga penganut anarkis – dirancang untuk membuat dusta seolah-olah kebenaran, menjadikan pembunuh seolah-olah manusia terhormat, dan angin hampa seolah-olah tampak padat.”
***
Ungkapan George Orwell itupun sebenarnya bukan untuk membenarkan suatu fakta bahwa politik tidak ada urusannya dengan kebenaran dan kejujuran. Justru sebaliknya, ungkapan itu adalah satire dan kritik tajam bahwa politikus dan partai-partai politik masih saja gagal menerapkan kejujuran dalam perilaku politik.
Demikian pula suasana batin yang sedang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Kita melihat dan merasakan bahwa kejujuran sepertinya sedang pergi meninggalkan bangsa ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengembalikan kejujuran sebagai nilai dasar berpolitik dan berperilaku sosial? Mengapa seruan-seruan dalam forum keimanan sekalipun gagal menghasilkan manusia-manusia yang jujur? Jika demikian, apakah kejujuran lebih terletak pada sistem dan bukan pada manusia? Sederet pertanyaan bisa diajukan untuk menggugat ketiadaan kejujuran.
Kejujuran bukanlah sebuah keutamaan moral yang berhenti setelah seseorang berhasil mencapainya. Kejujuran menuntut suatu usaha keras terus-menerus sepanjang waktu. Ketika hari ini kita jujur, tidak berarti kita menjadi manusia jujur karena atribut itu harus dibuktikan sepanjang waktu. Kesulitannya, situasi-situasi yang mengancam kehidupan atau eksistensi sering kali memaksa kita untuk mengabaikan, dan bahkan meninggalkan, kebenaran murni. Aktivitas politik termasuk dalam ranah yang mendorong politikus untuk berperilaku tidak jujur, itupun dengan lihai dibungkus dalam istilah ”white lies” alias berbohong demi kebaikan. Padahal sejatinya, berbohong demi kebaikan sama saja dengan paham menghalalkan segala cara. Kalau tujuan dipandang sebagai sesuatu yang benar, maka cara apapun boleh digunakan untuk mencapai tujuan itu, termasuk dengan berbohong.
Kembali pada persoalan politik. Apakah politik kejujuran dan kejujuran dalam politik sungguh-sungguh bisa menjadi nyata? Untuk menjawab pertanyaan itu, pertama-tama tentu perlu dipahami terlebih dahulu apakah politik itu. Kata “politik” adalah sebuah rumusan yang kompleks dan dinamis. Penjelasan paling mudah barangkali dengan meminjam ungkapan Kenneth Gergen (1999), yang mengatakan, dunia kita dibangun oleh kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan itu akan bisa berinteraksi dengan landasan kekuasaan.
Mengenai kekuasaan, Michel Foucault (1976) menulis bahwa kekuasaan diciptakanj dibuat melalui diskursus atau percakapan. Diskursus yang telah melembaga dalam institusi sosial-budaya itulah yang kemudian menciptakan norma-norma kekuasaan dan kontrol.
Wacana (discourse), menurut Foucault, dibuat dan diabadikan oleh mereka yang memiliki kekuatan dan sarana komunikasi. Menurut Foucault, kebenaran, moralitas, dan makna dibentuk melalui discourse itu.
Sampai di sini hendak dikatakan, kejujuran dalam politik bukan hanya terbatas pada persoalan sistem dan manusia. Kejujuran mencakup pula problem literasi terhadap diskursus. Sistem yang rigid bisa saja bocor ketika manusia-manusia baik (secara normatif) di dalamnya tidak mampu menafsirkan diskursus yang sedang berlangsung. Pemahaman Foucaultian ini agaknya penting untuk melengkapi upaya-upaya kita membangun sistem politik yang terlepas dari sifat-sifat buruknya. Kita menyadari, honesty is the best policy, dan itu dimulai dari proses diskursus terus-menerus tak kenal lelah.







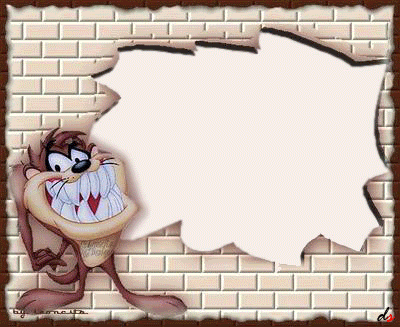
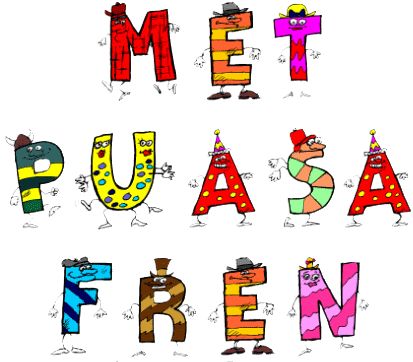































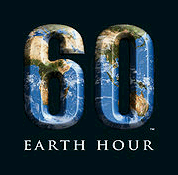












Tidak ada komentar:
Posting Komentar